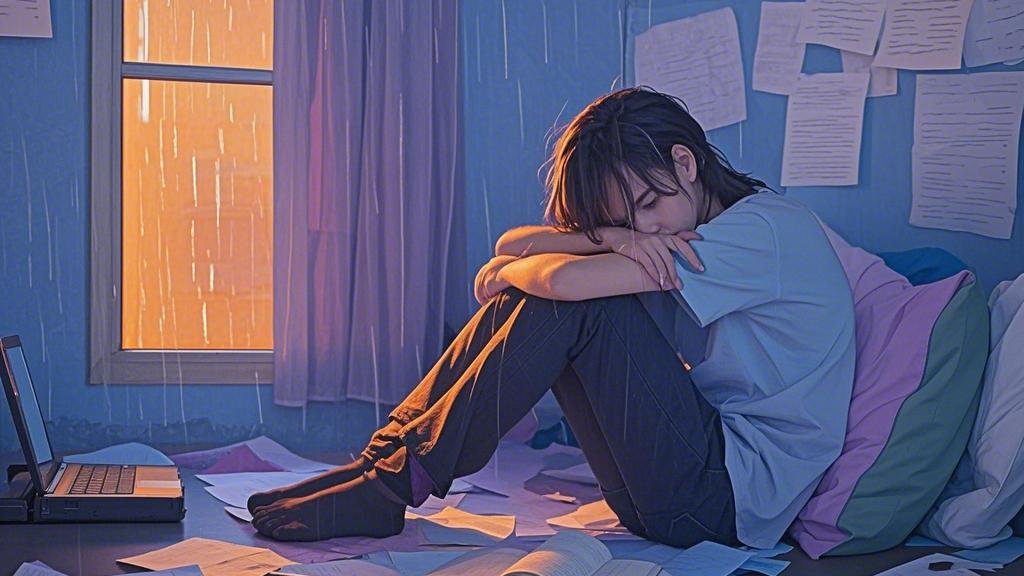Kemendukbangga/BKKBN — Porsi tangggung jawab pengasuhan anak — sejak dahulu hingga kekinian — lebih banyak diberikan kepada perempuan (baca = ibu). Alasan yang kerap didengar sungguh sangat klise: ayah sudah berperan mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga. Lantas, bagaimana dengan ibu pekerja, yang juga mencari nafkah untuk keluarga?
Sejatinya, keterlibatan peran ayah dalam pengasuhan anak mempunyai dampak positif yang besar. Masyarakat sendiri masih belum banyak yang terpapar mengenai hal tersebut. Statistik menunjukkan, masih banyak anak di Indonesia yang tumbuh tanpa kehadiran ayah atau fatherless dalam hidup mereka.
Berdasarkan data UNICEF 2021, sekitar 20,9% anak di Indonesia tidak memiliki figur ayah, baik karena perceraian, kematian, atau pekerjaan ayah yang mengharuskan mereka tinggal jauh dari keluarga. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun yang sama menunjukkan, hanya 37,17% anak usia 0–5 tahun dibesarkan oleh kedua orang tua lengkap.
Fenomena fatherless sendiri membawa dampak serius terhadap tumbuh kembang anak dan kesejahteraan keluarga. Situasi ini harus menjadi perhatian bersama, mengingat pentingnya kehadiran ayah dalam mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang seimbang, sehat dan harmonis.
Bahkan, berbagai penelitian menunjukkan, dengan keterlibatan aktif ayah dalam kehidupan anak, baik pada masa kanak-kanak maupun remaja, terbukti dapat memperbaiki kesehatan mental, hubungan sosial, dan prestasi akademis mereka.
Ayah yang terlibat secara positif dapat berperan sebagai panutan, pelindung, dan penyemangat dalam menghadapi berbagai tantangan anak di masa remaja.
Untuk itulah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN meluncurkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), guna mendorong penguatan peran ayah, terkhusus dalam pengasuhan agar tumbuh kembang anak maksimal untuk menuju Indonesia Emas 2045.
● Fatherless to be Fatherhood
Fenomena fatherless berpengaruh besar pada perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan psikologis anak. Konsekuensi dari kekurangan figur ayah dalam kehidupan anak sangat beragam, mulai dari masalah dalam membentuk identitas diri, kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, hingga perasaan kurangnya perlindungan dan dukungan emosional.
Anak yang tumbuh tanpa ayah juga berisiko lebih tinggi terlibat perilaku negatif seperti kecanduan, kekerasan, dan masalah mental.
Sebenarnya pengklasifikasi-an tugas ayah dan ibu tidak disadari sudah diajarkan kepada anak sejak dini. Taruhlah frasa “Ayah sedang bekerja, mencari uang”, atau “Ayah pulang lembur karena banyaknya pekerjaan di kantor”. Seringkali itulah jawaban ibu saat anak menanyakan ayahnya di mana dan sedang apa.
Secara tidak langsung sudah terpatri dalam benak anak bahwa tugas ayah itu mencari nafkah. Sebaliknya, ibu bertugas mengurus keluarga. Terbukti, saat anak menanyakan ibu di mana, acap kali dijawab “Ibu sedang memasak”, “Ibu sedang menyapu halaman”. Atau sedang melakukan tugas-tugas pekerjaan di rumah dan lingkungan sekitar.
Pengklasifikasi-an ini lantas memperoleh legalisasi, pada saat anak mulai mencicipi bangku sekolah. Tanpa disadari, di sekolah anak diajarkan perbedaan antara tugas seorang pria dan perempuan.
Pemahaman pengklasifikasi-an ini akan terekam, dan kelak akan menjadi salah satu pembenar, bahwa tugas dari seorang pria (baca=ayah) adalah mencari nafkah tanpa embel-embel terlibat dalam pengasuhan anak.
Untuk itu, perubahan pemahaman akan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak harus dilakukan terintegrasi dan masif. Tidak bisa seperti membalik telapak tangan, atau dengan cepat. Berubah menjadi sosok fatherhood membutuhkan pemahaman dan kelegowoan maskulinitas seorang pria.
● Pentingnya Kehadiran Emosional Ayah
Sudah seharusnya kita mulai menguatkan pentingnya kehadiran emosional ayah dalam kehidupan anak, serta mengajarkan pentingnya peran ayah dalam membentuk karakter anak-anak mereka.
Sejatinya, seorang pria mempunya sifat alamiah, yakni kasih sayang dan perhatian. Tindakannya melibatkan emosional. Pada dasarnya, rumah juga sebagai tempat bagi pria. Sehingga absennya pria dalam pengasuhan anak menjadi kurang tepat.
Pria harus memahami tentang pengasuhan dan perawatan anak, pekerjaan rumah tangga serta aktivitas-aktivitas lainnya. Hal ini kemudian memunculkan istilah fatherhood atau “kebapakan”, yakni bentuk maskulinitas yang melibatkan ayah untuk lebih bertanggung jawab pada hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak.
Fatherhood merupakan instrumen menuju suatu keintiman yang seringkali absen antara laki-laki (ayah) dan anak.
Maka, Gerakan Ayah Teladan Indonesia secara langsung memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran ayah dalam mengasuh anak. Program GATI sendiri melingkupi adanya: (1) Layanan Konseling Melalui Siap Nikah dan Satyagatra; (2) Konsorsium Penggiat dan Komunitas Ayah Teladan, seperti Komunitas Ayah ASI; (3) Desa/Keluraham Ayah Teladan di Kampung Keluarga Berkualitas; dan (4) Sekolah bersama Ayah di PIK-R Jalur Pendidikan dan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
● Merubah Doktrin
Perubahan konteks paradigm maskulinitas, khususnya dalam keluarga, membutuhkan peran serta seluruh pihak. Termasuk anggota keluarga, komunitas, dan masyarakat sekitar. Secara sederhana bersama-sama kita dapat memulai dengan merubah doktrin kepada anak, mengenai pembagian tugas ayah dan ibu dalam keluarga.
Ibu juga harus memberikan ruang kepercayaan, kesempatan, dan aktivitas kepada ayah, untuk bisa mendampingi aktivitas anak.
Keseluruhan program GATI dan kesungguhan tekad, diharapkan dapat mendorong secara masif perubahan pemahaman seorang pria mengenai pentingnya keterlibatan peran seorang pria (baca=ayah) dalam pengasuhan anak dan aktivitas keluarga.
Perubahan ini, mari kita mulai terlebih dahulu dari diri kita dan keluarga kita.**
Penulis: Rahmitasari Prastriyani
Editor: Humas/Media Center*
Foto: BKKBN Jawa Tengah
Tanggal Rilis : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu: Pk. 20.30 WIB
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK
Media Center Kemendukbangga/BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Instagram: kemendukbangga_bkkbn
Facebook: BKKBN
Twitter/X: @kemendukbangga
TikTok: kemendukbangga_bkkbn
Snack Video: kemendukbangga_bkkbn
YouTube: kemendukbangga_bkkbn
www.kemendukbangga.go.id
Tentang Kemendukbangga/BKKBN
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kemendukbangga/BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.